Asratillah (Direktur Profetik Institute)
Antara angka dan realitas kota
Pemerintah Daerah mana yang tak gemar memamerkan angka-angka? Begitu pula dengan Pemerintah Kota Makassar. Baru-baru ini, Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar sudah menyentuh 83,53—kategori tinggi dan membanggakan. Rata-rata lama sekolah 11,6 tahun, angka harapan hidup 71 tahun. Statistik itu ibarat baliho besar di jalan raya, terang-benderang, indah dipandang mata, namun sering kali gagap menjawab keluhan warga.

Air bersih, misalnya. RPJMD 2025–2029 mengungkap kebutuhan tahunan air bersih Makassar mencapai 1,38 miliar meter kubik, sementara pasokan yang tersedia hanya 575 juta meter kubik. Defisit 808 juta meter kubik air bersih, bukanlah persoalan sepele. Tak jarang warga lorong antri sambil menenteng jeriken, memompa sumur bor yang mungkin saja tercemar, atau menunggu truk tangki PDAM yang datang tidak tentu. Angka IPM bisa naik, tetapi keran di rumah tetap kering.
Sanitasi juga mengandung ironi. Akses sanitasi layak pada 2024 memang sudah di angka 88,66 persen, tetapi jika dipatok pada sanitasi aman, angka itu jatuh menjadi hanya 5,7 persen rumah tangga. Sebagian besar warga masih bergantung pada septic tank seadanya, atau langsung membuang limbah ke saluran terbuka. Kota ini mencatat kemajuan di atas kertas, tapi di bawah tanah, kotoran tetap mengendap dan mencemari air dan tanah.
Rumah layak huni? Dokumen resmi mencatat proporsinya sudah mencapai 80,39 persen pada 2024. Rumah Tidak Layak Huni tinggal 0,1 persen. Tetapi di sisi lain, kawasan kumuh masih meluas hingga 299 hektar—sekitar 1,69 persen luas kota. Kawasan kumuh ini bukan sekadar rumah reyot, melainkan akumulasi kerentanan, sanitasi buruk, drainase tersumbat, banjir yang berulang. Dari Panakkukang hingga Tamalate, dari Tamalanrea hingga Tallo, kawasan kumuh adalah wajah kota yang belum beres.
Banjir sendiri menjadi drama tahunan. Infrastruktur pengendali memang sudah ada, kolam regulasi Nipa-Nipa seluas 84 hektar, waduk Pampang seluas 42,5 hektar, kanal-kanal besar. Namun, sedimentasi, enceng gondok, dan sampah membuat semua itu bersoal. RPJMD memang mencatat 100 persen kawasan rawan banjir telah terlindungi infrastruktur, tetapi warga tetap merasakan genangan di jalan, rob di pesisir, dan luapan sungai di bantaran rumah.
Ruang kota dalam dokumen adalah satu hal, ruang kota yang dijalani sehari-hari adalah hal lain. Angka-angka pembangunan manusia di Makassar mengilustrasikan paradoks, indeks naik, tetapi kehidupan tetap rapuh. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi?
Kota sebagai karya kolektif
Henri Lefebvre dalam The Production of Space (1974/1991) menggugat anggapan lama bahwa ruang hanyalah wadah kosong yang bisa diisi dengan apapun. Baginya, ruang adalah hasil dari relasi kuasa, ekonomi, dan simbol yang saling bertarung. Ruang selalu diproduksi, direproduksi, dan ditafsirkan. Ia bukan sesuatu yang natural, melainkan konstruksi sosial yang penuh kepentingan. Lefebvre menulis, “(Social) space is a (social) product”—ruang selalu lahir dari proses sosial, dan karena itu ia sarat kontradiksi.
Untuk memahami kontradiksi itu, Lefebvre menawarkan apa yang ia sebut triadik ruang. Praktik ruang adalah pengalaman sehari-hari yang dialami tubuh manusia, berjalan di lorong sempit, bekerja di pasar, berteduh dari hujan, mencari air, atau bahkan sekadar menunggu angkutan. Ruang di sini bukan ide, melainkan kenyataan yang dijalani.
Representasi ruang adalah bagaimana para perencana, teknokrat, dan birokrat membingkai ruang dalam peta, dokumen, atau masterplan. Ia adalah ruang yang diidealkan, dipetakan, diproyeksikan. Sedangkan ruang representasional adalah ruang yang penuh makna simbolik dan imajinatif, ruang protes, ruang doa, ruang yang dikelola komunitas untuk menegaskan identitasnya. Konflik kota lahir ketika representasi ruang menindih praktik ruang dan mengabaikan ruang representasional.
Lefebvre mengingatkan bahwa bahasa teknis perencanaan, dengan grafik dan peta yang tampak objektif, justru sering menyingkirkan pengalaman nyata warga. Peta jalan bisa tampak rapi, tetapi tubuh yang berjalan di trotoar yang sempit merasakan yang sebaliknya. Masterplan bisa menampilkan kota yang indah, tetapi kehidupan di lorong-lorong mengungkap wajah lain yang jauh dari ideal. Inilah kontradiksi produksi ruang, sebuah ketegangan antara yang diidealkan dari atas dan yang dijalani dari bawah.
Dalam perspektif ini, pembangunan manusia tidak bisa hanya dibaca melalui indikator-indikator formal. Ia harus dilihat sebagai proses produksi ruang, bagaimana kebijakan, modal, dan kekuasaan membentuk ruang kota, dan bagaimana warga meresponsnya dalam kehidupan sehari-hari. Ruang adalah arena di mana kuasa bekerja, dan karena itu pula, ruang adalah arena di mana perlawanan bisa lahir. Lefebvre menekankan bahwa representasi ruang selalu mencoba mendominasi, tetapi ruang representasional—ruang simbol, budaya, dan perlawanan—selalu menemukan cara untuk menegaskan dirinya.
Henri Lefebvre, dalam Le Droit à la Ville (1968), mengajukan gagasan yang kini banyak dipakai sebagai panji gerakan perkotaan, yakni “hak atas kota”. Bagi Lefebvre, kota bukan hanya sekadar ruang tinggal atau pusat ekonomi, tetapi medan hidup yang kompleks, di mana manusia mencari makna, identitas, dan kebersamaan. Hak atas kota, karenanya, bukan sekadar hak untuk menempati sebidang lahan atau memperoleh layanan publik dasar. Ia adalah hak untuk berpartisipasi dalam membentuk, menikmati, dan menafsirkan kota. Lefebvre menulis bahwa hak atas kota berarti dua hal yang saling terhubung, “hak untuk mengakses” dan “hak untuk mengubah”.
Akses berarti setiap orang berhak menikmati ruang kota, mulai dari air bersih, ruang publik, transportasi, perumahan, ruang budaya. Tetapi akses saja tidak cukup. Hak atas kota juga mencakup hak untuk mengubah, artinya warga berhak terlibat dalam proses produksi ruang itu sendiri, apakah keterlibatan dalam merancang, memutuskan, dan menafsirkan apa makna ruang bagi mereka. Kota bukan hanya milik perencana atau investor, melainkan milik semua orang yang hidup di dalamnya.
Dalam kerangka ini, angka-angka pembangunan manusia yang sering dirayakan pemerintah hanyalah bentuk parsial dari hak atas kota. IPM yang tinggi tidak otomatis berarti warga benar-benar memiliki hak atas kota, jika mereka tidak bisa ikut menentukan bagaimana ruang kota dikelola. Infrastruktur bisa dibangun, tetapi jika warga tidak terlibat, ruang itu akan terasa asing. Lefebvre menegaskan bahwa kota tidak boleh direduksi menjadi sekadar objek konsumsi atau komoditas kapital, melainkan harus dipahami sebagai “oeuvre”—sebuah karya kolektif yang diciptakan dan dihidupi bersama.
Hak atas kota, pada akhirnya, adalah kritik terhadap logika kapital dan birokrasi yang mendominasi produksi ruang. Di banyak kota, termasuk di Indonesia, ruang diproduksi untuk melayani kepentingan investasi, reklamasi pantai, superblok, apartemen mewah. Sementara itu, ruang untuk warga miskin—kampung, lorong, ruang terbuka publik—dipinggirkan atau digusur. Lefebvre mengingatkan bahwa hak atas kota bukan hanya hak minoritas yang terpinggirkan, melainkan hak kolektif seluruh warga untuk menegaskan kembali kota sebagai ruang hidup bersama.
Kita bisa meminjam gagasan Bourdieu untuk memperkaya pembacaan. Jika Lefebvre bicara tentang produksi ruang dan hak atas kota, Bourdieu bicara tentang produksi habitus dan distribusi modal. Modal budaya, sosial, ekonomi, dan simbolik membentuk cara orang mengakses ruang. Habitus, dalam bahasa Bourdieu, adalah struktur yang mengendap di dalam tubuh, yang membuat seseorang merasa wajar melakukan sesuatu, merasa pantas berada di suatu tempat, atau justru merasa terasing.
Ia bukan sekadar kebiasaan, melainkan disposisi mendalam yang terbentuk oleh sejarah hidup. Pendidikan tinggi bisa memberi modal budaya dalam bentuk ijazah dan pengetahuan, tetapi tanpa modal sosial berupa jaringan relasi, ruang ekonomi tetap terkunci. Seorang sarjana yang tidak punya akses ke jaringan politik atau bisnis akan tetap terpinggirkan dari lapangan kerja yang menjanjikan.
Modal simbolik pun bekerja seperti kunci tak kasatmata, status, nama keluarga, atau reputasi bisa membuka pintu tertentu, tetapi tanpa habitus yang sesuai, seseorang tetap merasa kikuk di dalamnya. Di ruang rapat korporasi, misalnya, seseorang dengan modal budaya tinggi bisa saja paham teori, tetapi tanpa habitus yang membiasakan diri dengan bahasa tubuh dan kode sosial elite, ia tetap merasa menjadi orang asing.
Dalam kerangka ini, ruang kota bukan hanya dibatasi oleh tembok dan pagar, tetapi juga oleh tembok sosial yang dibangun dari distribusi modal. Ada mal atau kafe yang terasa “bukan untuk kita”, ada perumahan yang meskipun tidak bertuliskan “dilarang masuk” tetap menandai siapa yang pantas berada di dalam dan siapa yang tidak.
Bourdieu mengingatkan bahwa akses terhadap ruang selalu dimediasi oleh distribusi modal dan habitus. Lorong sempit, pasar tradisional, atau ruang publik kota bisa jadi ruang hidup yang ramah bagi sebagian orang, tetapi terasa penuh stigma bagi yang lain. Begitu pula sebaliknya, ruang elite bisa menjadi simbol aspirasi bagi kelas menengah, tetapi sekaligus menjadi arena pengucilan bagi mereka yang tidak memiliki modal simbolik untuk masuk. Kota dengan demikian adalah lanskap habitus yang bertubrukan, tempat di mana modal-modal yang berbeda dipertaruhkan, dan di mana rasa “pantas” atau “asing” terus diproduksi.
Membayangkan ulang kota
Pembangunan manusia hanya akan membumi bila ia diterjemahkan ke dalam ruang-ruang konkret. Angka IPM tidak akan berarti apa-apa jika keran air tetap kering, septic tank bocor, rumah kurang layak tuk dihuni, dan pemuda merasa frustrasi. Yang dibutuhkan Makassar bukan sekadar target angka, tetapi keberanian untuk membayangkan ulang kota sebagai ruang hidup bersama.
Mari bayangkan sebuah program yang tidak berhenti sebagai slogan belaka, melainkan benar-benar mengubah praktik ruang. Program itu bisa disebut Kampung Air dan Ruang Hidup, misalnya. Di kawasan Tallo, yang kerap menjadi langganan banjir sekaligus kekurangan air, dibangun sistem penampungan air hujan kolektif yang dikelola warga.
Di Panakkukang, drainase yang kerap tersumbat bisa diubah menjadi taman resapan, sehingga ruang publik dan infrastruktur saling berkelindan. Di Tamalanrea, mahasiswa yang punya banyak waktu luang bisa bermitra dengan nelayan untuk mengembangkan inkubator kerja berbasis keterampilan lokal, dari teknologi tepat guna untuk pengolahan ikan, hingga aplikasi digital untuk pemasaran hasil laut.
Ini bukan utopia kosong. Surabaya pernah membuktikan bahwa taman kota bisa menjadi ruang belajar dan rekreasi publik yang nyata. Bandung menunjukkan kampung kreatif bisa mengubah wajah kumuh menjadi sumber ekonomi baru. Jakarta dengan Kampung Akuarium memperlihatkan bahwa partisipasi warga dalam merancang hunian adalah mungkin. Makassar bisa belajar dari semua itu, tetapi dengan menambahkan imajinasinya sendiri, sesuai dengan karakter lorong, pesisir, dan masyarakat urban yang unik.
Lefebvre menyebut hak atas kota sebagai hak bukan hanya untuk tinggal, tetapi untuk membentuk, menikmati, dan mengatur ruang. Bourdieu mengingatkan bahwa modal budaya warga harus bisa dikonversi menjadi modal ekonomi, dan itu hanya mungkin jika ruang sosial mendukung. Maka pembangunan manusia di Makassar tidak bisa berhenti di ruang representasi berupa angka, tetapi harus mewujud dalam praktik ruang sehari-hari yang manusiawi, air bersih, sanitasi aman, rumah yang bermartabat, pekerjaan yang layak.
Angka IPM memang penting, tetapi hanya sebagai peta kasar. Jalan sejatinya adalah bagaimana kota diproduksi ulang agar benar-benar menjadi milik semua warganya. Pembangunan manusia baru bisa disebut berhasil jika seorang ibu di Tamalate bisa menyalakan keran air dengan tenang atau tidak mesti menunggu larut malam, seorang anak di Manggala bisa bermain di taman tanpa cemas banjir, dan seorang sarjana di Panakkukang bisa bekerja tanpa harus menyogok jaringan kuasa. Sampai saat itu tiba, pembangunan manusia hanyalah angka.


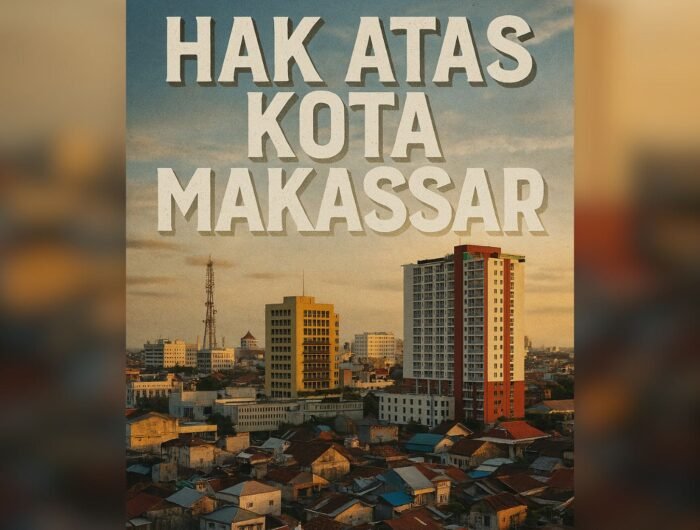








Comment