M. Yunasri Ridhoh (Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar)
Ketika Prabowo Subianto menang telak dalam Pilpres 2024 lalu, di mana mayoritas pemilihnya berasal dari generasi muda, tentu saja banyak yang tertegun. Bagaimana bisa, generasi yang tumbuh di tengah kebebasan pascareformasi justru memihak figur yang dulu diasosiasikan dengan masa otoritarian Orde Baru.

Apakah perbedaan generasi juga mempengaruhi perbedaan dalam memahami demokrasi? Soal ini, ada penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, dan Liam Gammon, berjudul “Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians” (2025).
Penelitian ini mencoba menelisik fenomena tersebut, hasilnya cukup mengejutkan, diungkap bahwa Gen Z Indonesia adalah generasi yang paling puas terhadap demokrasi. Ini tentu sesuatu yang aneh untuk tidak menyebutnya anomali, sebab di saat yang sama berbagai studi justru mengungkap bahwa kualitas demokrasi kita dalam satu dekade terakhir mengalami kemunduran signifikan.
Memoria generasi
Setiap generasi tentu memaknai demokrasi berdasarkan pengalaman sejarah dan konteks sosial yang membentuknya. Bagi generasi tua, seperti Baby Boomers (lahir tahun 1946-1964) dan Gen X (lahir tahun 1965-1980), demokrasi adalah buah dari perjuangan panjang melawan ketakutan dan represi. Mereka masih menyimpan memori tentang pembatasan berbicara, sensor media, militerisme, dan kekuasaan yang nyaris absolut di era Orde Baru.
Bagi mereka, demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan pengalaman moral-kultural, di mana semuanya harus diperjuangkan, misalnya hak untuk menyampaikan pendapat tanpa takut, untuk memilih tanpa paksaan, dan untuk mengkritik tanpa kehilangan pekerjaan. Karena itu, generasi ini lebih sensitif terhadap gejala kemunduran demokrasi. Mereka tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan.
Namun, bagi generasi yang lahir atau menjalani masa kecilnya setelah reformasi, terutama sebagian Generasi Y/Millennial akhir (lahir tahun 1981-1996) dan Gen Z (lahir tahun 1997-2012) demokrasi hadir bukan sebagai hasil perjuangan, melainkan sebagai kondisi default.
Mereka lahir di tengah kebebasan berpendapat, melihat pemilu langsung sebagai rutinitas, dan menganggap kebebasan berekspresi di media sosial sebagai sesuatu yang biasa saja. Demokrasi bagi mereka bukanlah cita-cita yang harus diperjuangkan, melainkan realitas sehari-hari yang dianggap akan selalu ada.
Problemnya, karena tak pernah mengalami ketiadaan kebebasan, mereka juga kehilangan rasa waspada terhadap ancaman yang bisa saja terulang atau terjadi kembali. Misalnya saat media dibungkam atau aktivis dikriminalisasi, banyak anak muda menganggapnya sekadar berita biasa, bukan tanda bahaya bagi masa depan demokrasi.
Dilema milenial dan problem gen Z
Generasi milenial menempati posisi transisi yang menarik. Mereka adalah saksi euforia reformasi pada akhir 1990-an, tetapi juga saksi bagaimana demokrasi pascareformasi tidak otomatis menghadirkan keadilan sosial. Mereka menyaksikan korupsi yang tetap marak, partai politik yang oligarkis, dan elitisme yang semakin kuat.
Dalam banyak survei, milenial menunjukkan tingkat kepercayaan yang menurun terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan. Mereka lebih percaya pada figur dibanding institusi. Ini menjelaskan mengapa politik personalistik begitu kuat, terutama di era media sosial. Politik bukan lagi soal ideologi, melainkan soal branding.
Namun, di tengah kekecewaan itu, milenial tetap memelihara nalar kritis. Mereka aktif di gerakan sosial, membangun komunitas digital, dan menginisiasi wacana-wacana alternatif di luar kanal formal politik. Dari mereka lah, kita belajar bahwa demokrasi tidak boleh hanya hidup di parlemen, tetapi juga di ruang-ruang kewargaan.
Hanya saja, idealisme itu kadangkala berbenturan dengan kenyataan ekonomi. Keterbatasan lapangan kerja, tekanan finansial, dan beban sosial yang membuat sebagian milenial mundur dari aktivisme ke pragmatisme. Berbeda dengan pendahulunya, Gen Z tumbuh dalam ruang publik digital yang serba cepat, visual, dan emosional.
Politik bagi mereka tidak lebih sekadar konten, bukan sesuatu yang mendesak dan penting. Fenomena “Gemoy” Prabowo pada kampanye 2024 menjadi contoh paling mencolok. Dalam penelitian Prof. Burhanuddin, dkk., branding yang lucu dan relatable terbukti lebih efektif menarik simpati Gen Z dibanding isu hak asasi manusia atau tata kelola pemerintahan.
Inilah wajah baru politik kita, algoritma menjadi kunci segalanya. Rasionalitas kadang dikalahkan oleh daya tarik emosional. Identitas digital lebih menentukan pilihan politik daripada ideologi kepartaian, apalagi ideologi kebangsaan. Dalam ruang semacam ini, demokrasi bergeser dari deliberation menjadi attention economy, atau dari ruang musyawarah menjadi pasar perhatian.
Namun, menariknya, Gen Z bukan generasi anti-demokrasi. Mereka tetap menganggap demokrasi sebagai sistem terbaik. Hanya saja, mereka tidak menganggap demokrasi sedang terancam. Mereka puas dengan yang ada, bahkan ketika kebebasan sipil dibatasi, hukum disubordinasikan, dan politik uang kian marak.
Kepuasan tanpa kesadaran inilah yang disebut para peneliti sebagai “demokrasi yang terbuai atau terlena”. Pertanyaannya, mengapa mereka terbuai, mengapa terlena? Ada beberapa kemungkinan. Paling tidak, faktor-faktur berikut bisa menjelaskan fenomena ini.
Pertama, demokrasi tanpa pendidikan kewarganegaraan yang kritis dan kontekstual akan melahirkan warga yang apatis. Itu pasti. Faktualnya kurikulum pendidikan kita cenderung menekankan hafalan nilai-nilai demokrasi tanpa mengajarkan pengalaman demokratis. Siswa diajarkan Pancasila, tetapi jarang diajak berdiskusi tentang isu-isu publik secara kritis.
Kedua, politik yang terlalu elitis membuat jarak antara warga dan negara semakin curam. Partai politik lebih sibuk memperjuangkan kekuasaan ketimbang aspirasi rakyat. Akibatnya, generasi muda merasa demokrasi adalah urusan “orang atas,” bukan ruang yang bisa mereka bentuk dan pengaruhi.
Ketiga, banjir informasi di dunia digital menciptakan paradoks kesadaran. Anak muda tahu banyak isu politik, tetapi tidak mendalaminya. Mereka mengonsumsi potongan-potongan narasi, bukan pengetahuan utuh. Akibatnya, kesadaran politik menjadi dangkal, cepat terbentuk, namun cepat pula dilupakan.
Mengusulkan demokrasi antar-generasi
Perbedaan cara pandang antar-generasi terhadap demokrasi tidak harus dilihat sebagai jurang, melainkan sebagai potensi. Generasi tua memiliki memori perjuangan; generasi milenial memiliki daya kritik; dan Gen Z memiliki energi kreatif. Bila ketiganya disinergikan, demokrasi Indonesia akan memiliki akar yang dalam sekaligus sayap yang lebar.
Untuk itu, perlu upaya sungguh-sungguh membangun “literasi demokrasi lintas generasi”. Bukan sekadar menghafal definisi demokrasi dan beragam teori demokrasi, tetapi memahami bagaimana demokrasi bekerja, dan bagaimana ia bisa keropos dan gagal. Kampus, media, dan lembaga masyarakat sipil harus menjadi ruang di mana sejarah, kritik, dan kreativitas berjumpa.
Sebagaimana diingatkan oleh ilmuwan politik Nancy Bermeo (2016), ancaman terhadap demokrasi modern tidak hanya datang dari kudeta militer atau revolusi, tetapi dari “democratic backsliding”, yaitu kemunduran perlahan, yang memang kadang tak disadari karena dibungkus stabilitas dan popularitas.
Nah, di sinilah peran generasi muda menjadi penentu, apakah mereka akan menjadi penjaga demokrasi, atau sekadar penonton yang puas meski di tengah kemerosotan? Demokrasi Indonesia hari ini sedang kehilangan kewaspadaan etisnya. Ia berjalan dengan prosedur, tapi melemah dalam substansi. Kita masih punya pemilu, tapi kehilangan daya kritis. Kita tentu masih punya kebebasan, tapi sering membiarkannya direduksi menjadi sekadar hiburan.
Maka, tantangan terbesar bagi generasi muda bukan lagi memilih antara demokrasi dan otoritarianisme, melainkan memilih antara kesadaran dan ketidakpedulian. Karena seperti kata Hannah Arendt, “bahaya terbesar bagi kebebasan bukanlah tirani, melainkan keengganan manusia untuk berpikir.”
Di tangan berbagai generasi, khususnya generasi muda, dengan kreativitas digitalnya, kecerdasannya, dan keberaniannya, demokrasi Indonesia bisa diperbarui. Tapi itu hanya mungkin jika mereka berhenti menjadi “penonton” yang puas, dan mulai menjadi warga yang sadar.


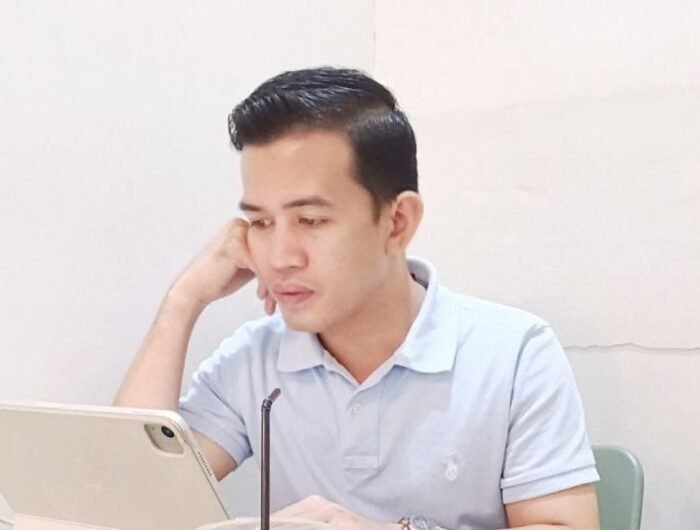








Comment