Respublica— Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah, dengan jeda maksimal dua tahun enam bulan, mengundang beragam respons dari berbagai kalangan.
Ada yang mengapresiasi keberanian MK menata ulang sistem pemilu demi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan demokrasi elektoral, namun tidak sedikit pula yang mengkritik langkah MK sebagai bentuk pelebaran wewenang, bahkan berpotensi menyalahi prinsip pembagian kekuasaan.

Antara koreksi dan kreasi norma
Dalam teori ketatanegaraan klasik, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai negative legislature. Sebuah konsep yang diperkenalkan Hans Kelsen untuk menjelaskan bahwa lembaga yudisial tidak berwenang membuat norma baru (kreasi), melainkan hanya membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi (koreksi).
Peran MK dalam sistem hukum Indonesia pun diatur tegas dalam Pasal 24C UUD 1945: menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa hasil pemilu, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan perselisihan antarlembaga negara.
Namun dalam praktiknya, beberapa putusan MK belakangan ini tampak melangkah lebih jauh, menyerupai positive legislature. Dalam putusan uji materi soal usia calon presiden dan wakil presiden, misalnya, MK bukan hanya menafsirkan konstitusionalitas norma, tetapi juga menyisipkan norma baru: memperbolehkan calon yang belum genap berusia 40 tahun, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Hal serupa terjadi dalam putusan terbaru terkait keserentakan pemilu. MK juga tidak lagi sekadar menilai konstitusionalitas model yang ada, tapi justru menetapkan sendiri pola pelaksanaan pemilu ke depan.
Pertanyaannya, apakah MK sedang menjawab kekosongan legislasi yang tak ditangani eksekutif dan legislatif, ataukah sedang memperluas wewenangnya secara sepihak?
Pertanyaan ini penting, karena kita khawatir akan terjadi, apa yang dikatakan oleh Ran Hirschl yaitu juristocracy, suatu keadaan di mana lembaga yudisial mengambil alih ruang-ruang politik representatif melalui produksi norma, yang sebentulnya bertentangan dengan semangat demokrasi.
Inkonstistensi dan implikasi
Yang menambah problematika adalah inkonsistensi MK sendiri. Dalam Putusan MK sebelumnya, Nomor 55/PUU-XVII/2019, MK telah memberikan ruang kepada DPR dan Pemerintah untuk menentukan model pemilu serentak dari enam opsi yang tersedia.
Model inilah yang kemudian dipakai dalam Pemilu 2024. Tapi dalam putusan terbaru, MK tampak mengambil alih keputusan tersebut dan secara eksplisit memerintahkan pemilu nasional dan daerah dilakukan terpisah dengan jarak tertentu.
Padahal, dalam banyak perkara strategis lain, MK kerap menolak untuk mencampuri proses legislasi menyangkut teknis dengan alasan open legal policy, yakni kebijakan hukum terbuka, yang merupakan hak eksklusif pembentuk undang-undang.
Secara praktis, putusan ini juga menyisakan persoalan teknis dan politis. Misalnya, sebagian besar kepala daerah dan DPRD hasil Pilkada 2024 akan mengakhiri masa jabatan pada 2029, sementara pemilu daerah baru akan berlangsung pada 2031.
Artinya, akan ada kekosongan kepemimpinan daerah selama dua tahun. Kekosongan ini kemungkinan besar akan diisi oleh penjabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat.
Meskipun secara hukum diakui, namun dari perspektif legitimasi demokrasi, kehadiran Pj selama dua tahun penuh rentan dipersoalkan. Pemerintahan yang tidak lahir dari proses elektoral cenderung administratif dan minim representasi.
Situasi lebih rumit terjadi di legislatif daerah. Kita tidak mengenal mekanisme Pj DPRD. Kekosongan ini berisiko membuat fungsi legislasi dan pengawasan daerah terhenti total.
Dari sisi konstitusi, hal ini juga bermasalah. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Jika pemilu DPRD digelar dua tahun setelah masa jabatan habis, maka asas legal certainty dalam kerangka negara hukum menjadi kabur.
Menjaga dialog konstitusional
Dalam sistem demokrasi konstitusional, pembagian kekuasaan dirancang bukan untuk saling membatasi secara kaku, melainkan untuk membangun kerja sama yang saling menghormati demi menegakkan konstitusi. Dalam hal ini, DPR dan Pemerintah memegang kewenangan dalam proses legislasi, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penguji konstitusionalitas atas produk legislasi.
Namun, agar relasi antar-lembaga ini tetap sehat dan fungsional, dibutuhkan mekanisme dialog konstitusional yang terbuka dan saling melengkapi. Putusan MK seyogianya dibaca sebagai bentuk kepekaan terhadap persoalan teknis dalam pelaksanaan pemilu serentak, seperti kelelahan administratif dan kejenuhan penyelenggara, pemilih dan peserta pemilu.
Akan tetapi, kepekaan itu tidak seharusnya berkembang menjadi tindakan yang justru melampaui kewenangannya dengan mengambil alih fungsi legislasi. Menjaga keseimbangan antara kehendak memperbaiki sistem dan batas konstitusional adalah kunci dari tata kelola demokrasi yang sehat. Dengan kata lain menjaga agar tidak ada satu lembaga pun yang merasa paling tahu atau paling berkuasa.





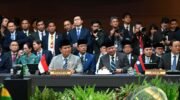





Comment