Oleh : Muh. Asratillah S (Direktur Profetik Institute)
Kemunculan demos
Viralnya pengibaran bendera bajak laut One Piece di sejumlah tempat bukan sekadar peristiwa fandom, tetapi sebuah artikulasi simbolik yang mengguncang tatanan “police“, jika meminjam kosa kata Jacques Ranciere. Dalam berbagai analisis, baik dari Drone Emprit, Kompas, BBC Indonesia, hingga pakar hukum tata negara, fenomena ini dibaca dalam spektrum mulai dari ekspresi spontan hingga potensi subversif.

Tapi jika kita menyusuri lebih jauh, pengibaran bendera One Piece—yang dibawa dari fiksi ke ruang publik—merupakan kemunculan demos, mereka yang tdak terhitung, menyatakan diri di hadapan tatanan yang kadang mambatasi ruang politik.
Menurut laporan Drone Emprit, rentang minggu pertama Agustus 2025, ada sebanyak 14.182 mentions perihal percakapan bendera One Piece di media sosial, seperti X, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, hingga media online.
Terdapat lebih dari 2.000 unggahan media sosial yang menggunakan tagar #BenderaLuffy dan #MerdekaVersiRakyat, dengan sekitar 68% unggahan mengandung sentimen kritik sosial terhadap pemerintah dan elite politik. Sisanya merupakan ekspresi humor, seni, atau identifikasi fandom terhadap karakter-karakter One Piece.
Menurut Ranciere, politik sejati terjadi saat mereka yang selama ini dianggap sebagai noise—bukan voice—mengklaim ruangnya dalam publik. Inilah yang ia sebut sebagai kemunculan demos, kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak memiliki bagian dalam tatanan sosial, kini menyatakan eksistensinya melalui tindakan-tindakan simbolik.
Dalam konteks bendera One Piece, pengibarannya dapat dibaca sebagai tindakan politik dalam makna Rancierian, yakni sebagai proses subyektivasi politik yang menginterupsi tatanan sosial dominan—atau yang ia istilahkan sebagai “police“. Police adalah struktur yang menciptakan partisi, menentukan apa yang terlihat dan tidak terlihat, siapa yang didengar dan siapa yang dibungkam.
Ketika simbol seperti bendera bajak laut dikibarkan di ruang publik, ia tidak hanya mengganggu estetika yang mapan, tetapi juga mendesak ulang distribusi kesensibelan (distribution of the sensible), yakni apa yang layak didengar, dilihat, dan dianggap sah sebagai bagian dari ruang politik.
Dalam pemikiran Jacques Rancière, distribusi kesensibelan adalah tatanan tak tertulis yang menentukan pembagian indrawi, siapa yang dapat tampil di ruang publik, apa yang boleh dikatakan, dan bagaimana sesuatu bisa diartikan sebagai ‘politik’.
Simbol non-negara seperti bendera bajak laut menabrak batas ini, karena ia memperkenalkan kategori baru dari pengalaman politik—yang berasal dari ranah fiksi, fandom, dan budaya populer—ke dalam lanskap yang sebelumnya hanya diisi oleh simbol-simbol formal kenegaraan.
Dengan munculnya simbol ini, warga seakan-akan mendeklarasikan diri, kami juga hadir, kami juga merasa, dan kami juga layak bicara. Ia mendobrak batas konvensional antara yang politis dan yang non-politis. Maka, bendera bajak laut bukan sekadar gangguan visual, tetapi juga aksi politik yang menantang ‘pembagian inderawi’ yang selama ini mengecualikan ekspresi budaya rakyat dari ranah politis.
Ini adalah ekspresi dari ketegangan demokrasi kontemporer, antara estetika resmi negara dan estetika emergen rakyat yang menuntut untuk diakui sebagai bagian dari representasi politik yang sah. Bendera bajak laut, yang dalam narasi One Piece adalah simbol perlawanan terhadap rezim yang dianggap korup, menjadi metafora kuat bagi keresahan kolektif di dunia nyata.
Ia menjelma menjadi bentuk pernyataan bahwa ada warga negara yang merasa tak dihitung, tak diwakili, dan tak didengar. Dalam kacamata Ranciere, tindakan ini bukanlah makar atau sikap anti-negara, tetapi cara warga untuk memverifikasi kesetaraan yang selama ini diacuhkan oleh tatanan dominan.
Ini bukan bendera negara lain, bukan pula lambang organisasi makar. Ia adalah simbol estetika-politik yang menantang pembagian hierarkis tentang siapa yang punya hak untuk tampil dan menyuarakan pendapat di ruang bersama. Maka, dalam setiap kibaran bendera ini, terdapat penolakan atas logika eksklusi, dan sekaligus pembukaan kemungkinan baru bagi munculnya ruang demokrasi yang lebih setara nan dinamis.
Dengan bingkai ini, peristiwa One Piece bukanlah sekadar hiburan atau pelanggaran hukum. Ia adalah “gangguan” terhadap tatanan sosial dominan, tempat negara terlalu terbiasa pada simbol-simbol tunggal (bendera negara, lambang instansi) dan menganggap semua simbol lain sebagai noise.
Ini mirip dengan gagasan Ranciere tentang politik sebagai perselisihan, bukan menggulingkan negara, tapi menginterupsi makna dominan tentang apa itu kewargaan, apa itu nasionalisme, dan siapa yang punya hak bicara di ruang publik.
Antara sinyal harapan dan gagapnya negara
Jika Ranciere menyoroti gangguan dalam estetika sosial, Jurgen Habermas menawarkan cara pandang lain, tindakan komunikatif dalam ruang publik. Dalam teori demokrasi deliberatifnya, komunikasi bukan sekadar ekspresi, melainkan proses rasional untuk menemukan pemahaman bersama.
Dalam konteks pengibaran bendera One Piece, publik—khususnya kaum muda—tengah mengirim sinyal simbolik, ada keresahan, ada ketidakpercayaan terhadap simbol-simbol formal negara, ada jarak yang melebar antara institusi dan imajinasi warga.
Sayangnya, alih-alih ditanggapi dengan dialog deliberatif, banyak respons negara justru mengambil bentuk represif atau minimalis. Dalam kacamata Jurgen Habermas, tindakan negara seperti ini mencerminkan kegagalan membentuk ruang publik yang sehat, di mana warga dapat menyampaikan ekspresi dan pendapat secara bebas dalam kerangka tindakan komunikatif.
Negara semestinya hadir sebagai fasilitator diskursus, bukan sebagai pemilik tunggal makna atau pengontrol simbol. Dalam logika deliberatif Habermas, negara hanya dapat membenarkan otoritasnya jika mampu terlibat dalam diskusi terbuka dan rasional dengan warganya, serta menerima bahwa keabsahan (legitimitas) kebijakan publik bersumber dari proses komunikasi yang bebas dari dominasi.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Menurut laporan Amnesty International Indonesia, aparat keamanan melakukan razia dan penyitaan bendera One Piece di setidaknya empat kota besar yakni Tuban, Sragen, Tangerang, dan Yogyakarta. Bahkan, beberapa warga dilaporkan mengalami intimidasi atau dipaksa menghapus unggahan WhatsApp dan Instagram mereka.
Respons semacam ini memperlihatkan bagaimana negara masih memelihara logika kekuasaan administratif daripada logika diskursif. Dalam konteks ini, ruang publik tidak difungsikan sebagai arena deliberasi, tetapi sebagai ruang yang harus dijaga steril dari bentuk ekspresi yang dianggap tidak sesuai dengan narasi resmi. Ini adalah bentuk patologis dari komunikasi, ketika kekuasaan mendominasi interaksi sosial, dan menggantikan argumentasi dengan paksaan simbolik.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Menteri HAM menyatakan bahwa pelarangan ini merupakan upaya menjaga stabilitas nasional, meski tidak merinci pasal hukum yang dilanggar. Sikap ini menunjukkan bahwa negara masih gagap menghadapi simbol-simbol baru yang lahir dari warga dan bukan dari lembaga resmi.
Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang tidak didominasi negara atau pasar, tempat warga bisa bicara setara. Bendera One Piece seharusnya bisa dibaca sebagai ajakan berdiskusi, bukan dimusuhi. Tapi pemerintah tampak belum siap menghadapi simbol-simbol baru yang tidak lahir dari lembaga resmi. Ini menunjukkan absennya “kecakapan komunikasi” negara untuk terlibat dalam diskursus yang melibatkan bentuk ekspresi simbolik.
Demokrasi menemukan denyutnya
Kritik publik adalah nafas demokrasi. Fenomena One Piece, dalam sudut pandang ini, bisa dibaca sebagai kritik yang berselimut humor, sebagai energi sipil yang menunjukkan harapan. Dalam kacamata Ranciere, ini adalh bentuk politik sejati, ketika warga yang tak diperhitungkan memunculkan dirinya melalui simbol yang mengejutkan, tak lazim, dan penuh ironi.
Pengibaran bendera bajak laut adalah bentuk gangguan terhadap tatanan simbolik yang selama ini dianggap normal, dan karenanya membuka celah politik yang memperluas horizon demokrasi. Demokrasi, menurut Ranciere, justru hidup dari momen-momen perselisihan seperti ini—saat logika formal kewargaan diganggu oleh praktik-praktik yang tak terduga tapi bermakna.
Sementara dari sudut pandang deliberatif, seperti yang dikemukakan Habermas, simbol semacam ini bisa menjadi titik masuk menuju diskursus yang lebih luas. Humor dan simbol populer adalah bentuk tindakan komunikatif awal—ia memancing perbincangan, mengundang tafsir, dan membuka potensi deliberasi. Dalam masyarakat yang apatis, orang tidak lagi repot-repot menggantungkan bendera apa pun.
Tapi saat ada yang mengibarkan bendera bajak laut, justru di situlah demokrasi menemukan denyutnya, sebab warga sedang mengaktifkan kembali ruang publik sebagai arena komunikasi. Hal ini sejalan dengan gagasan Habermas bahwa revitalisasi demokrasi mensyaratkan ruang publik yang inklusif, di mana bentuk-bentuk komunikasi yang tidak konvensional pun tetap dipandang sah dan bernilai politis.
Dalam analisis hukum yang dimuat oleh Hukumonline, salah satu pakar dari UII menyatakan bahwa selama Merah Putih tidak diganti secara struktural atau diturunkan, maka tidak ada dasar hukum pidana untuk memproses pengibaran bendera fiksi seperti Jolly Roger dari One Piece. Pernyataan ini diperkuat oleh pakar hukum tata negara dari UGM yang menyebut bahwa tindakan warga tersebut justru merupakan ekspresi simbolik sah atas rasa tidak puas terhadap praktik pemerintahan.
Bendera One Piece bukan soal anime. Ia adalah soal siapa yang berhak mengisi ruang publik, siapa yang dianggap pantas bicara, dan bagaimana negara mendengar tanpa merasa terancam. Ini bukan soal setuju atau tidak pada simbol itu, tapi apakah demokrasi kita cukup dewasa untuk menampung perbedaan gaya berpendapat, cara bersuara, dan bentuk harapan.
Saat negara mengejar bendera, ia sesungguhnya sedang dikejar oleh pertanyaan, apakah kamu masih mampu mendengar wargamu sendiri? Esai ini mengajak kita tidak hanya melihat simbol, tetapi mendengar suara di baliknya.








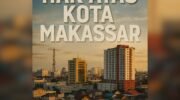


Comment