M. Yunasri Ridhoh (Dosen Pendidikan Kewarganegaraan FEB UNM)
Ribuan massa tumpah ruah di jalan pada Jumat, 29 Agustus 2025. Kota berubah menjadi lautan manusia yang menuntut keadilan. Anehnya, di tengah arus demonstrasi besar itu, aparat kepolisian tak tampak hadir. Tidak ada barisan pagar betis, tidak ada kendaraan taktis, bahkan sekadar mengatur lalu lintas pun tak ada. Sebuah momentum langka, tak pernah terjadi sebelumnya.

Bagi saya ini seharusnya dikelola dan dimafaatkan untuk membuktikan bahwa rakyat dapat mengelola dirinya sendiri, dengan berunjuk rasa dengan baik.
Namun, tampaknya tidak demikian yang terjadi. Demonstrasi yang semula teratur, pecah menjadi amukan massa. Pos keamanan dibakar, kendaraan dibakar, kantor parlemen diserbu, dibakar dan dijarah. Tentu ini debatable, sebab disituasi tertentu ini bisa dibenarkan. Tapi yang tragis karena, beberapa staf sipil yang bekerja di kantor parlemen tersebut kehilangan nyawanya.
Kekacauan ini lalu membentuk framing publik, bahwa kepolisian adalah institusi yang mutlak dibutuhkan. Bahwa tanpa mereka, negara akan terjerumus pada kekacauan. Narasi lama kembali diulang—“lihat, tanpa polisi Indonesia bisa bubar.” Padahal, ada paradoks besar yang tersembunyi di balik logika itu.
Kekacauan sebagai politik
Kerusuhan bukan sekadar insiden spontan. Ia sering kali adalah puncak dari akumulasi kekecewaan, dari kemarahan atas korupsi yang dibiarkan, arogansi dan kemewahan pejabat yang dipertontonkan, kebijakan yang mencekik rakyat kecil. Dalam situasi stagnan, di mana kanal-kanal aspirasi publik tersumbat, jalanan menjadi arena terakhir. Sayangnya, ekspresi politik yang lahir dari kekecewaan itu mudah diseret ke dalam jebakan politik kekacauan.
Kekacauan memberi pembenaran bagi negara untuk mempertahankan aparat represif. Dengan kerusuhan, kepolisian tampil sebagai “penyelamat” yang tak tergantikan. Masyarakat pun diarahkan pada keyakinan bahwa tanpa polisi, tanpa senjata, tanpa kekerasan negara, republik ini akan karam.
Inilah politik kekacauan—sebuah logika di mana kerusuhan justru menguntungkan kekuasaan. Negara mendapatkan pendasaran sosiologis baru untuk mengontrol, sementara akar masalah yang sesungguhnya—korupsi, kesenjangan, dan ketidakadilan—tetap dibiarkan.
Faktanya kerap kali luput dari pembahasan kita mengenai mengapa kerusuhan itu terjadi. Narasi resmi hanya menyorot pada api dan asap, bukan pada bara yang menyulutnya.
Padahal masyarakat tidak pernah turun ke jalan hanya karena ingin membakar mobil atau kantor parlemen. Mereka turun karena ada frustrasi yang menumpuk: tentang pejabat yang hidup dalam kemewahan di tengah rakyat yang kesulitan, tentang peraturan yang dipermainkan demi kepentingan elite, tentang anggaran negara yang diperlakukan bak harta warisan pribadi.
Ironinya, daya rusak perilaku elite sebetulnya dan senyatanya lebih dahsyat ketimbang massa yang marah. Korupsi sistematis merampas hak kesehatan, pendidikan, hingga masa depan generasi. Kebijakan yang diskriminatif menyingkirkan kelompok tertentu dari ruang hidup yang layak. Tetapi, kerusakan yang terjadi di ruang birokrasi dan parlemen jarang disebut sebagai “kerusuhan.”
Ujian demokrasi
Peristiwa 29 Agustus itu adalah ujian bagi demokrasi kita. Apakah negara akan menjawabnya dengan refleksi dan perbaikan, atau sekadar dengan menambah pasukan, menebalkan tameng, dan mengeraskan pentungan?, ujungnya tambah personil, tambah anggaran keamanan.
Tugas kepolisian seharusnya bukan sekadar menjaga “ketertiban” dalam arti sempit, tetapi juga menjadi penjaga rasa aman publik. Rasa aman tidak lahir dari intimidasi, melainkan dari keadilan. Tidak ada keamanan sejati bila korupsi merajalela. Tidak ada ketertiban sejati bila hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Di sisi lain, masyarakat juga harus bercermin. Kemarahan yang meluap-luap sering kali menghancurkan tujuan itu sendiri. Aksi yang berakhir dengan pembakaran justru memudahkan kekuasaan untuk menggeser isu. Alih-alih membicarakan korupsi dan arogansi pejabat, publik digiring untuk membicarakan kerusuhan.
Indonesia tidak boleh terus-menerus dikendalikan oleh politik kekacauan. Relasi antara rakyat, aparat, dan penguasa harus ditata ulang. Negara perlu membuka kanal partisipasi politik yang sehat dan bermakna, bukan membiarkannya tersumbat hingga meledak di jalanan. Kepolisian pun harus memperbaiki diri, dari alat kekuasaan menjadi pengayom yang dipercaya warga.
Lebih dari itu, elite politik perlu menyadari, bahwa setiap keputusan yang mereka buat bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan soal kehidupan rakyat. Semakin mereka mempermainkan aturan dan anggaran, semakin mereka menyulut amarah yang berpotensi meledak sewaktu-waktu, ibarat bom waktu.
Peristiwa 29 Agustus tak boleh berhenti sekadar soal massa yang marah, juga bukan sekadar soal absennya polisi. Tetapi tamparan bagi pemerintah bahwa kontrak sosial kita kian retak. Bahwa rakyat merasa dikhianati, bahwa aparat dipersepsikan hanya hadir untuk kepentingan penguasa, dan bahwa negara lebih sibuk mengelola kekacauan daripada mengelola keadilan.
Ya, selama ketidakadilan tetap dipelihara, politik kekacauan akan selalu menemukan panggungnya. Dan setiap kali api itu berkobar, yang hangus bukan hanya gedung dan kendaraan, tetapi juga kepercayaan publik pada demokrasi. Atau itukah yang kita inginkan?




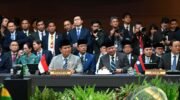






Comment