Di sebuah kafe, tampak enam orang pemuda begitu khusyuk mendengarkan ceramah dari seseorang tentang betapa bangsatnya negara ini. Dilihat dari tampangnya yang agak tua, barangkali ia senior mereka. Ia menyebut praktik korupsi yang merajalela, kemiskinan di mana-mana, oligarki yang dibiarkan bebas menguras kekayaan negara, hingga pemerintah yang tak becus mengurus rakyatnya.
“Lalu kenapa semua orang diam melihat ketimpangan ini?” katanya dengan nada berapi-api, khas aktivis yang baru saja lulus Latihan Kader Lanjutan. “Karena sistem dengan sengaja membuat masyarakat tidak kritis. Terjadi pembodohan sistemik yang membuat orang tidak sadar bahwa mereka sedang ditindas.”

Puncak ceramahnya adalah soal pencerahan dan penyadaran. Ia berharap anak-anak muda yang kritis dan sadar akan situasi tunggang langgang ini mau terlibat aktif mengedukasi masyarakat agar pikirannya terbuka dari kesadaran palsu. Ia meminjam tesis Karl Marx tentang ideologi.
Saat itu saya sibuk mengerjakan tugas kantor di laptop. Sesekali saya menguping dan menikmati ocehan pria gondrong yang penuh semangat itu. Tesis-tesisnya terdengar masuk akal. Bahkan, dulu saya juga percaya pada cara berpikir seperti itu. Namun, satu hisapan rokok kemudian membuat saya merenung agak lama, sambil mengistirahatkan mata yang lelah setelah berjam-jam menatap layar.
Sejumput pertanyaan tiba-tiba muncul: mungkinkah di era keterbukaan informasi seperti sekarang, masyarakat sebodoh itu hingga tak tahu kondisi hidupnya yang karut-marut? Atau jangan-jangan kita sebenarnya tahu persis apa yang dikeluhkan pemuda itu, hanya saja orang-orang justru menikmati kondisi tersebut dengan riang gembira?
Situasi ini mengingatkan saya pada hal-hal yang kita temui sehari-hari. Koruptor tahu korupsi adalah sifat tercela, tetapi tetap saja mereka melakukannya. Anies Baswedan tahu praktik demokrasi di Indonesia busuk, tetapi tetap ikut nyapres dan menikmati pemilu yang sering ia kritik. Orang-orang tahu toleransi penting, tetapi tetap saja mereka jadi bajingan rasis setiap kali bertemu etnis minoritas.
Barangkali tesis Slavoj Žižek layak dipertimbangkan untuk menjelaskan perubahan cara kerja ideologi hari ini. Jangan-jangan, ideologi tidak bekerja di level pengetahuan, tetapi di level tindakan. Sebab, menurut Žižek, cara kerja ideologi di dunia modern telah mengalami pergeseran. Model klasik ideologi sebagai kesadaran naif sudah tidak memadai lagi.
Ideologi kontemporer justru beroperasi melalui nalar sinis, yang ditopang oleh fantasi yang tidak disadari. Gagasan ini dijelaskan oleh Žižek dalam bukunya The Sublime Object of Ideology (2008). Ia memulai dari formula klasik ideologi sebagai kesadaran palsu ala Marx: Mereka tidak mengetahuinya, tetapi mereka melakukannya. Formula ini mengandaikan adanya kesadaran naif yang keliru mengenali realitas sosial.
Contohnya, buruh percaya majikannya baik, orang miskin percaya sistem ini adil, padahal realitasnya jauh dari itu. Kritik ideologi klasik, karena itu, bertujuan mencerdaskan subjek demi membongkar kepalsuan agar orang sadar bagaimana sistem sebenarnya bekerja. Namun, Žižek menganggap formula ini tidak relevan lagi.
Menurutnya, formula ideologi hari ini, mereka tahu betul apa yang mereka lakukan, tetapi tetap saja melakukannya. Inilah yang disebut Zizek sebagai nalar sinis. Orang-orang sebenarnya sadar akan jarak antara topeng dan realitas sosial. Tapi kesadaran itu sama sekali tidak menghalangi mereka untuk terus berpartisipasi dalam ritus ideologis.
Contohnya adalah fetisisme uang. Dalam kehidupan sehari-hari, individu tahu bahwa uang hanya ekspresi dari relasi sosial dan bukan perwujudan magis kekayaan. Namun, dalam aktivitas pertukaran komoditas, mereka bertindak seolah-olah uang secara inheren adalah perwujudan kekayaan. Mereka, kata Žižek, adalah “fetisis dalam praktik, bukan dalam teori”.
Akibatnya, kritik ideologi yang hanya berupaya “membuka kedok” menjadi tumpul. Subjek sinis sudah tahu sejak awal bahwa ada kedok, dan ia baik-baik saja dengan itu. Singkatnya, Žižek ingin mengatakan begini: ideologi hari ini tidak bekerja karena kita bodoh atau tertipu. Ia bekerja secara efektif justru karena kita sudah tahu semuanya, namun tetap menjalaninya. Di sinilah terjadi pembalikan penting dalam cara memahami ideologi.
Untuk menjelaskan hal ini, Žižek mengidentifikasi tiga momen dialektis dalam operasi ideologi. Pertama, ideologi dalam dirinya sendiri, yakni sebagai kumpulan gagasan, keyakinan, atau doktrin. Kedua, ideologi untuk dirinya sendiri, ketika ia mengambil bentuk material melalui institusi dan mekanisme sosial, seperti Aparatus Negara Ideologis dalam pengertian Althusser.
Ketiga, ideologi dalam dan untuk dirinya sendiri, yakni saat ia beroperasi secara efektif dalam praktik sosial sehari-hari. Momen ketiga inilah yang menjadi titik sentral pemikiran Žižek. Ia mengalihkan fokus dari apa yang orang katakan tentang keyakinannya ke bagaimana keyakinan itu terwujud secara material baik dalam praktik, ritual, dan objek-objek sehari-hari.
Žižek mengilustrasikan tesis ini melalui sejumlah contoh provokatif dalam The Plague of Fantasies (2008), yang menunjukkan bagaimana ideologi beroperasi dalam materialitas eksternal. Dalam buku tersebut, ia menawarkan analisis yang jenaka sekaligus tajam terhadap tiga tipe toilet: Jerman, Prancis, dan Anglo-Saxon.
Toilet Jerman, dengan lubang di depan, memungkinkan inspeksi tahi sebelum dibuang, mencerminkan ketertarikan kontemplatif yang ambigu. Toilet Prancis justru menempatkan lubang di bagian belakang, sehingga tahi segera disingkirkan tanpa perlu dilihat. Sementara toilet Anglo-Saxon yang berisi air mengambil jalan tengah: tahi tetap terlihat, tetapi tidak untuk diperiksa atau dipikirkan lebih jauh.
Bagi Zizek, masing-masing toilet tersebut mengandaikan suatu persepsi ideologis tertentu: ketelitian reflektif (Jerman), ketergesaan revolusioner (Prancis), dan pragmatisme utilitarian (Inggris). Dalam istilah politik, triad ini dapat dibaca sebagai konservatisme Jerman, radikalisme revolusioner Prancis, dan liberalisme Inggris.
Mudah bagi sang aktivis di kafe tadi untuk mengklaim dirinya tidak percaya pada ideologi apa pun, atau merasa telah bersikap kritis terhadap ideologi politik dominan saat ini. Namun, begitu ia mengunjungi toilet setelah menceramahi junior-juniornya, ia kembali tenggelam dalam ideologi. Itulah mengapa ritual eksternal jauh lebih menentukan secara ideologis daripada keyakinan internal.
Orang yang merasa menjaga jarak kadang tidak sadar bahwa ritual itulah yang telah menguasainya. Seperti kata Blaise Pascal: berlututlah, bertindaklah seolah-olah engkau percaya, dan keyakinan akan datang dengan sendirinya. Ini seperti seseorang yang tidak perlu percaya pada kapitalisme untuk berpartisipasi di dalamnya. Karena tindakannya dalam pertukaran komoditas sudah cukup untuk menopang semesta ideologis tersebut.
Lalu, bagaimana ideologi bisa bekerja efektif dalam praktik, padahal kita merasa sudah kritis? Žižek menjawabnya melalui pendekatan psikoanalisis Lacanian: ideologi itu ditopang oleh fantasi. Dalam kerangka pemikiran Žižek, fantasi memiliki fungsi ganda. Pertama, ia berperan sebagai layar yang menutupi kengerian sejati dari peristiwa dengan menghadirkan citra masyarakat sebagai keseluruhan organik yang harmonis.
Dalam konteks tersebut, fantasi memungkinkan kita tetap menjalankan ideologi dengan membuat ketidakadilan dapat ditoleransi, dan sistem terasa normal. Kondisi ini memungkinkan kita tetap hidup dan berfungsi. Tanpa fantasi, praktik ideologis akan terasa kejam, absurd, dan sulit dijalani. Kedua, fantasi berfungsi sebagai kerangka yang menstrukturkan realitas sosial dengan cara mengajari kita bagaimana cara berhasrat,
Agar mekanisme ini dapat dipahami dengan lebih jernih, perlu dibedakan terlebih dahulu antara pengertian fantasi dalam bahasa sehari-hari dan pengertian fantasi dalam kerangka teoretis Žižek. Umumnya fantasi dipahami sebagai angan-angan. Seseorang misalnya, menginginkan perempuan tetapi gagal mendapatkannya. Lalu ia berfantasi, bercumbu dengannya di sebuah kamar hotel. Fantasi, dalam arti ini, dianggap sebagai kompensasi atas kegagalan di dunia nyata.
Namun, fantasi yang dimaksud Žižek bukan pelarian dari realitas yang tak tertahankan. Fantasi merupakan mekanisme fundamental yang membentuk dan mengonstruksi hasrat itu sendiri. Karena itu, persoalannya bukan bahwa seseorang menginginkan perempuan lalu, karena gagal memperolehnya, ia berfantasi menikmati tubuhnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana seseorang tahu sejak awal bahwa ia menginginkan perempuan itu?
Di sinilah fantasi bekerja dengan memberi alasan bagi hasrat tersebut. Jadi, pada dasarnya kita tidak lahir dengan daftar keinginan yang sudah jelas. Fantasilah yang menunjuk objek penyebab hasrat—objet petit a dalam istilah psikoanalisis. Objek ini dipandang sebagai sesuatu yang layak diinginkan, meskipun pada akhirnya kepuasan sejati tidak pernah benar-benar tercapai.
Hal ini terlihat jelas dalam pengalaman jatuh cinta. Kita sering mengira cinta muncul secara spontan. Padahal, dalam diri kita sudah ada pola fantasi, semacam gambaran tak sadar tentang sosok seperti apa yang bisa memicu hasrat kita. Ketika kita bertemu seseorang yang kebetulan sesuai dengan pola tersebut, perasaan cinta pun muncul.
Mekanisme yang sama juga berlaku pada ideologi. Ia bekerja dengan membentuk fantasi tertentu: gambaran tentang bagaimana dunia seharusnya, apa yang dianggap wajar, dan siapa yang layak disalahkan. Dengan cara ini, fantasi mengatur apa yang terasa masuk akal untuk diinginkan dan dilakukan. Karena itu, kita bisa saja sadar bahwa suatu sistem tidak adil, tetapi selama sistem tersebut masih cocok dengan kerangka fantasi, kita tetap menjalaninya.
Namun, penjelasan ini masih terlalu sederhana untuk memahami fantasi dalam kerangka pemikiran Žižek. Fungsi fantasi tidak berhenti pada pembentukan hasrat individual semata. Žižek menegaskan bahwa fantasi pada dasarnya bersifat intersubjektif. Hasrat yang dipentaskan dalam skenario fantasi bukanlah hasrat murni subjek, tetapi hasrat Yang Lain (The Other).
Oleh karena itu, pertanyaan yang memicu hasrat bukanlah “Apa yang saya inginkan?”. Subjek dikonstruksi di sekitar pertanyaan Lacanian yang penuh teka-teki: Che vuoi?, apa yang kau inginkan dariku? Analisis Žižek atas fantasi putri Freud yang memakan kue stroberi menegaskan dimensi intersubjektif fantasi tersebut.
Ketika anak perempuan itu makan dengan lahap, ia menyadari bahwa orang tuanya sangat puas melihatnya. Dengan menikmati kue tersebut, sang anak berusaha menjadi objek hasrat orang tuanya. Dalam hal ini, fantasi menempatkan subjek sebagai objek penyebab hasrat Yang Lain, sesuatu dalam diri subjek yang membuatnya berharga di mata Yang Lain.
Masalahnya, dalam pertanyaan Che vuoi? subjek merasakan tuntutan dari Yang Lain, tetapi tidak pernah tahu persis apa yang diinginkan darinya. Di sinilah fantasi memainkan peran kunci. Ia berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan Che vuoi? Ia menyusun skenario imajiner untuk mengisi kekosongan hasrat Yang Lain dengan menyediakan kerangka naratif tentang apa yang diinginkan Yang Lain dari kita.
Dalam ideologi Nazi, misalnya, fantasi tentang “konspirasi Yahudi” berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan, “Apa yang sebenarnya diinginkan tatanan sosial dariku?”. Fantasi ini mengarahkan hasrat subjek pada perjuangan melawan figur “Yahudi”, sekaligus bekerja sebagai penjelasan imajiner atas ketidakpuasan struktural yang dialami subjek.
Ketidakpuasan tersebut—kemiskinan, krisis ekonomi, dan kecemasan identitas—sebenarnya bersumber dari kontradiksi sosial yang kompleks. Namun, fantasi ideologis menyederhanakannya dengan menghadirkan figur Yahudi sebagai objek penyebab gangguan, seolah-olah ada pihak tertentu yang menikmati sesuatu yang seharusnya milik kita.
Untuk lebih mudah memahami cara kerja fantasi ideologis, saya akan menggunakan analogi cerdas dari Žižek melalui Pokémon Go dalam esainya Ideology Is the Original Augmented Reality. Mekanisme inti gim ini sederhana namun efektif. Dengan memanfaatkan GPS dan kamera ponsel, Pokémon Go menampilkan makhluk virtual seolah-olah hadir di ruang dunia nyata.
Ruang publik seperti taman, jalanan, dan sudut kota yang sebelumnya biasa saja berubah menjadi arena perburuan. Menurut Žižek, apa yang dieksternalisasi oleh teknologi Pokémon Go adalah mekanisme dasar ideologi itu sendiri. Dengan bingkai fantasi dari layar digital, pemain termotivasi untuk menjelajah, menangkap, dan berinteraksi. Ideologi bekerja dengan cara seperti itu.
Ia menyajikan entitas-entitas semu yang memberi makna dan tujuan pada realitas sosial yang membingungkan, sekaligus mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan kerangkanya. Sebagaimana ideologi Nazi yang secara efektif menawarkan kerangka fantasi kepada masyarakat Jerman, sehingga mereka melihat figur Yahudi di mana-mana.
Tahu kan, Presiden Prabowo Subianto kerap mendengung-dengungkan soal “kekuatan asing” setiap kali berpidato? Tujuannya jelas. Cerita ini berfungsi sebagai jawaban sederhana atas pertanyaan, “Apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat dariku?” Jawabannya dirumuskan tegas dan lugas: konspirasi asing, itulah yang mereka inginkan!
Figur aneh ini dimunculkan semata-mata sebagai penjelasan atas ketidakpuasan yang dialami masyarakat terhadap kondisi sosial ini, sembari menutupi antagonisme sosial yang sebenarnya bersifat struktural. Dengan memproyeksikan sumber masalah pada “kekuatan asing”, fantasi ideologis bekerja menciptakan ilusi bahwa masyarakat sebenarnya harmonis, hanya saja terganggu oleh kehadiran unsur luar tertentu.
Maka, jika kesenjangan sosial di Indonesia makin parah, itu pasti ulah antek asing. Secara sadar, orang bisa saja berkata, “Prabowo sedang ngibul.” Namun, dalam praktiknya, setiap kali muncul sosok yang rajin mengkritik pemerintah, bergaya hidup liberal, atau nyinyir terhadap perilaku kolot masyarakat kita, fantasi tentang “konspirasi asing” tetap dibutuhkan. Melalui fantasi itu, semua yang tidak disukai bisa dengan mudah dilihat sebagai antek-antek asing.
Bahkan, dalam kondisi paling ekstrem, fantasi semacam ini bisa mendorong seseorang menjadi bajingan rasis, dengan memandang etnis asing di Indonesia sebagai biang berbagai persoalan. Misalnya, ada seorang Tionghoa yang membuka bisnis kafe, menciptakan lapangan kerja, mengelola usahanya dengan rapi, dan bersikap baik kepada lingkungan sekitar.
Alih-alih bersimpati lalu membuang jauh-jauh cerita tentang konspirasi asing, fantasi malah menyusun narasi aneh namun dibutuhkan untuk memuaskan hasrat: jangan-jangan semua kebaikan si Cina itu justru menjadi bukti bahwa konspirasi asing memang nyata, jangan-jangan si antek asing ini sedang berupaya menguasai negara kita.
Praktik penafsiran inilah yang menunjukkan bahwa ideologi tetap hidup. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa ideologi hadir dalam tindakan-tindakan kecil sehari-hari. Padahal, semua itu adalah realitas tambahan dari fantasi ideologis untuk melapisi kontradisi sosial yang sebenarnya. Lalu kita menjalaninya dan menikmatinya, meski kita sudah lelah dengan realitas menyedihkan dalam hidup ini.
Muhajir MA, Jurnalis dan Pemerhati Filsafat


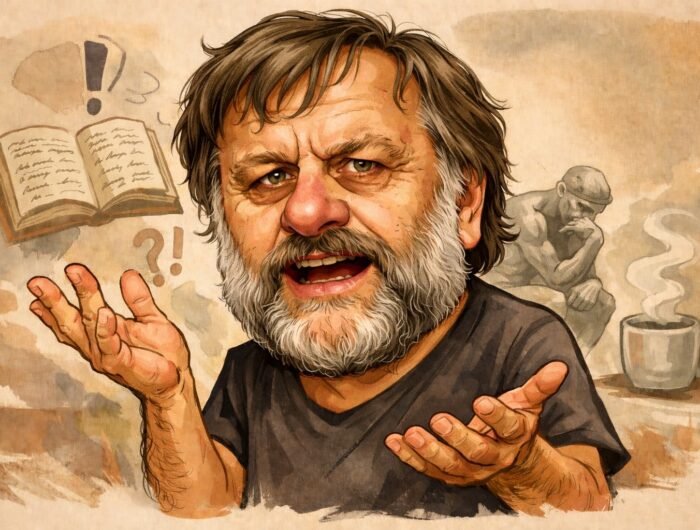








Comment